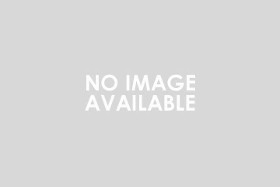
Seni dan Sensor: Perjalanan Kritik di Tembok
Tidak butuh waktu lama bagi sebuah negara untuk menghapus kritik yang muncul dari dinding. Pada 8 September 2025, di dinding Queen’s Building, sisi Carey Street dari kompleks Royal Courts of Justice, London, Banksy menempelkan adegan yang tidak membutuhkan teks: seorang hakim berwig dan berjubah hitam membungkuk, palu (gavel) terangkat, siap menghantam seorang demonstran yang tergeletak. Sang demonstran berupaya melawan dengan menahan papan protes putih sebagai perisai; permukaannya terciprat merah—satu-satunya warna dalam komposisi monokrom—seakan darah yang belum mengering.
Dua hari kemudian, 10 September, petugas pembersih menyikat dinding itu bersih. Dalih resmi: pelestarian bangunan bersejarah. Fasad kembali rapi. Tetapi “ghost image” yang tertinggal di kepala publik justru makin tebal: bukan lagi tentang gambar, melainkan tentang kecepatan negara menutup mulut ruang publik.
Di sinilah paradoks yang ingin diuraikan: sensor bukan sekadar penghapus, ia bekerja sebagai kurator yang tak diundang. Ia memilih mana yang digarisbawahi, mana yang menjadi legenda, dan mana yang, ironisnya, semakin hidup setelah disapu bersih. Dan penting untuk menegaskan sejak awal—bahwa ini bukan protes terhadap kota. Yang dituding bukan dinding. Yang dipersoalkan adalah negara: kebijakannya, refleksnya, ketakutannya; cara ia melindungi simbol, menutup mata sambil menutup telinga dari kritik publik.
Beberapa pekan sebelum London, pantulan adegan itu muncul di Yogyakarta. Di Triharjo, Sleman, dua mural bergambar Jolly Roger—ikon bajak laut Topi Jerami dari One Piece—dipersoalkan karena dianggap melecehkan bendera; penghapusan dilakukan pada 7 Agustus 2025, disaksikan aparat. Di Balecatur, mural serupa yang dibuat pemuda kampung sejak 25 Juli juga ditimpa cat hitam pada malam yang sama setelah musyawarah kilat. Tetapi tembok jarang benar-benar diam: pada permukaan yang sama kemudian muncul kalimat-kalimat sederhana—“Kebenaran akan terus hidup”, “Kita ada dan berlipat ganda”—seakan dinding membalas dengan napasnya sendiri. Di jantung kota Yogyakarta, 31 Agustus 2025, Jembatan Kewek menyajikan tulisan “Reset Menggila(s)”; sehari sesudahnya, 1 September, Pojok Beteng Wetan melontarkan “Awas Intel.” Dalam hitungan dua–tiga hari, semua lenyap oleh tangan-tangan tak dikenal. Tetapi seperti di London, yang hilang dari dinding justru tumbuh di linimasa: foto, video pendek, dan percakapan yang menolak dibungkam.
Mengapa ini penting? Karena seni tak pernah turun ke jalan dalam situasi normal. Ketika lukisan keluar dari galeri, ketika kata-kata berpindah ke tembok, ketika musik disiarkan dari ruang-ruang kecil lalu ditarik paksa, itu pertanda darurat. Bukan darurat ketertiban, melainkan darurat keadilan. Darurat ketika keputusan negara menyakiti dan mengecewakan warganya; ketika penjelasan tak lagi memadai, ketika ruang dengar menguncup, ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman. Seni lalu mengambil alih peran sirene: pendek, keras, tak bisa diabaikan.
Mari menajamkan lensa pada tiga lapis: visual, hukum, dan kebijakan.
Lapisan Visual
Banksy memilih gavel—palu sidang—sebagai ikon pukulan hukum. Di Inggris & Wales, gavel bukan bagian dari praktik persidangan; ia lebih hidup sebagai klise media dan simbol “impor”, sementara—di luar pengecualian seremonial oleh petugas di satu pengadilan—hakim tidak menggunakannya dari bangku. Ketidakselarasan tanda itu bukan kekeliruan, melainkan strategi semiotik: ikon salah tempat yang membuat pesan terbaca global—kekuasaan hukum, di mana pun, dapat berubah menjadi pukulan simbolik. Satu-satunya warna merah pada plakat demonstran menjadi pusat pandang—titik luka—menandai bahwa yang diserang bukan hanya tubuh warga, melainkan teks protesnya. Penempatan di Carey Street, tepat di kompleks peradilan, mengubah tembok menjadi alamat: kritik dikirim langsung ke jantung institusi. Komposisi tegas, ekonomis, menghunjam. Maka, ketika mural itu disapu atas nama heritage, publik menangkap kalimat lain: batu dilindungi, suara diredam.
Lapisan Hukum
Di Inggris, Royal Courts of Justice berstatus bangunan terdaftar (Grade II). Pengubahan yang berdampak pada karakter bangunan—termasuk pembersihan agresif pada permukaan bersejarah—umumnya memerlukan listed building consent dalam kerangka Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 dan pedoman Historic England. Di sisi lain, Eropa juga memegang Pasal 10 European Convention on Human Rights tentang kebebasan berekspresi: negara boleh membatasi, tetapi dengan uji ketat—legalitas, tujuan sah, dan kebutuhan serta proporsionalitas. Kita bisa berdebat lama soal penerapan uji ini, namun minimal pertanyaan publik sah adanya: adakah cara yang lebih proporsional daripada menyikat habis dalam 48 jam—misalnya memindahkan ke panel sementara, memberi waktu baca, atau setidaknya mendokumentasikan dengan standar konservasi yang setara dengan nilai sejarah fasad?
Di Indonesia, kerangka hukumnya lain, namun resonansinya sama. Mural One Piece dipersoalkan lewat tafsir UU 24/2009 (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara)—sensitivitas simbolik yang sering dibaca secara maksimalis di tingkat komunitas. Di ranah digital dan performatif, UU ITE (perubahan 2024) dengan pasal penghinaan yang dipindahkan ke 27A, dan horizon KUHP 2023 (UU 1/2023) yang akan mengaktifkan kembali pasal penghinaan presiden (mulai 1 Januari 2026), menciptakan chilling effect—efek gentar yang membuat musisi menarik lagu, panitia membatalkan pentas, galeri menutup pintu. Padahal Indonesia menandatangani ICCPR Pasal 19: setiap pembatasan ekspresi harus memenuhi uji tiga serangkai—berbasis hukum, bertujuan sah, dan perlu serta proporsional. Pertanyaan kebijakan yang tajam, karenanya, bukan “bolehkah dilarang?”, melainkan “sepadankah larangan itu dengan risiko yang hendak dicegah? Adakah alternatif dengan dampak yang lebih ringan terhadap kebebasan berekspresi?”
Lapisan Kebijakan
Di balik setiap penghapusan ada rantai insentif: kebijakan pusat yang ingin menjaga “kendali narasi”, birokrasi heritage/ketertiban yang alergi risiko, aparat yang mengejar indeks keteraturan, komunitas lokal yang dijejali kepanikan simbolik menjelang upacara nasional. Rantai ini menghasilkan refleks yang sama: “hapus dulu, jelaskan belakangan.” Padahal di ekosistem digital, hukum algoritma bekerja terbalik. Setiap penghapusan adalah panggung baru; setiap pelarangan adalah promosi tak sengaja. Efek ini bukan slogan: ia diamati bertahun-tahun—disebut Streisand effect—upaya menutup sesuatu justru melambungkan perhatian dan memperpanjang umur pesan.
Sejarah memberi cermin yang lebih pekat. Pada 1937 di Jerman, pameran Entartete Kunst dipakai rezim untuk mempermalukan dan menyingkirkan ribuan karya yang dicap “merosot”; sebagian dijual untuk devisa, sebagian dimusnahkan. Di Soviet, sejak 1932, doktrin socialist realism memaksa seni memasang wajah heroik proletariat, sementara yang tidak sejalan disingkirkan ke pinggir. Indonesia memiliki lukanya sendiri: penulis dan seniman beraliran realisme sosialis diburu dan dipenjarakan; nama-nama dibuang ke Pulau Buru, buku-buku dilarang beredar. Kita tidak menyamakan zaman dan sistem politik itu dengan hari ini—itu akan ahistoris. Tetapi kita mengakui pola yang berulang: negara yang rapuh cenderung mengatur selera, bukan mendengar isi.
Setahun terakhir memberi contoh nyata di sini dan kini. 19 Desember 2024, pameran Yos Suprapto di Galeri Nasional Jakarta dibatalkan pada hari pembukaan; pintu ruang pamer digembok, alasan “teknis” diumumkan, substansi diseret ke pinggir. 15–16 Februari 2025, pementasan Payung Hitam “Wawancara dengan Mulyono” dibatalkan di kampus seni; studio dikunci, poster dicabut. 20 Februari 2025, band punk Sukatani dipaksa menarik lagu “Bayar Bayar Bayar” dan meminta maaf di depan kamera karena menyinggung institusi kepolisian. Di tengahnya, Kamisan tetap berdiri: payung-payung hitam sebagai alfabet duka yang tak berhenti mengeja nama-nama yang menuntut keadilan. Semua ini bukan protes pada kota. Ini teguran pada negara: cara membuat kebijakan, cara merespons kritik, cara menata perbedaan.
Jika tujuan kita adalah menjaga keadaban bersama, maka jawaban tidak bisa berhenti pada sapu, gembok, dan pasal. Kita butuh standar baru yang membuat wibawa dan dialog berhenti menjadi pilihan biner.
Lima Langkah untuk Menciptakan Ruang yang Lebih Sehat
Pertama, permukaan sementara di situs sensitif. Panel-panel legal yang boleh dicat di perimeter bangunan heritage atau kantor publik. Ketika karya muncul di fasad utama, pemindahan ke panel—bukan penghapusan—memberi jeda baca 3–7 hari, lalu pelepasan terhormat. Dengan begitu, batu terlindungi, suara terdengar.
Kedua, dokumentasi wajib sebelum pelepasan. Foto 3D/4K, metadata waktu, konteks, dan jika mungkin keterangan dari pembuat atau pemilik dinding. Arsip ini harus terbuka—semacam heritage of dissent—agar kota menyimpan jejak perdebatan, bukan hanya kilau fasadnya.
Ketiga, forum 48 jam. Alih-alih “hapus dulu”, buat mekanisme pertemuan singkat antara kurator, perwakilan institusi, seniman/komunitas, dan aparat. Hasilnya—alasan hukum, opsi kebijakan, mitigasi risiko—diumumkan publik. Ini tidak selalu mengubah keputusan, tetapi mengubah cara keputusan itu dipahami.
Keempat, pedoman respons lintas-medium. Mural bukan teater; musik bukan aksi diam. Tiap medium memiliki risiko dan ruang lingkupnya. Pedoman singkat—mudah dibaca, dievaluasi—membedakan kritik yang menyelamatkan dari ujaran kebencian, satire dari fitnah, ketidaknyamanan dari bahaya. Ini memupus dalih “semua sama”—dalih yang sering dipakai untuk menyingkirkan yang paling getir.
Kelima, ukur yang bisa diukur. Jika pemerintah sungguh ingin tampil percaya diri, tetapkan indikator: rata-rata waktu respons (jam), proporsi kasus yang dide-eskalasi tanpa penghapusan, jumlah pernyataan resmi yang mencantumkan dasar hukum dan alasan proporsionalitas, jumlah open walls legal per tahun, jumlah sesi forum 48 jam yang terdokumentasi. Wibawa yang terukur selalu lebih tahan guncang dibanding wibawa yang hanya mengandalkan cat baru.
Pada akhirnya, pilihan kita sederhana meski sulit. Kita bisa terus menjadikan sensor sebagai kurator utama—membiarkan ketakutan mengarsipkan karya mana yang diingat. Atau kita bisa memindahkan kendali kurasi itu kembali ke tempat yang lebih sehat: akal budi, empati, dan keberanian untuk mengubah pikiran ketika bukti menuntut. Negara yang kuat bukan yang cepat menghapus, melainkan yang sanggup mengelola kritik tanpa panik; yang menjaga tembok dan merawat suara; yang memahami bahwa setiap mural yang muncul adalah laporan singkat dari lapangan—tentang kebijakan yang tidak tepat sasaran, penegakan yang menyakiti, atau rasa marah, kecewa rakyat yang dibiarkan membusuk.
Sebab demokrasi tidak diukur dari seberapa bersih dindingnya, melainkan dari seberapa luas ia menampung suara yang tidak menyenangkan. Dan jika suara itu memilih tembok sebagai mimbar—seperti di Carey Street pada 8 September, seperti di Kewek pada 31 Agustus, seperti di Pojok Beteng Wetan pada 1 September, seperti di Sleman pada 7 Agustus—maka itu bukan ancaman. Itu peringatan. Peringatan bahwa yang diminta bukan kosmetik kebijakan, melainkan koreksi arah. Bahwa yang dicari bukan ruang sunyi, melainkan ruang dengar.
Tembok boleh dibersihkan. Tetapi suara sukar dimatikan. Yang bisa kita tentukan adalah apakah kita akan mendengarnya sekarang, ketika ia masih berupa cat tipis di dinding, atau nanti, ketika ia telah menjelma gema panjang yang menggetarkan fondasi. Jika “ketika sensor menjadi kurator” adalah bab kita hari ini, maka bab besok—jika kita memilihnya—bisa berjudul lain: ketika negara belajar mendengar.



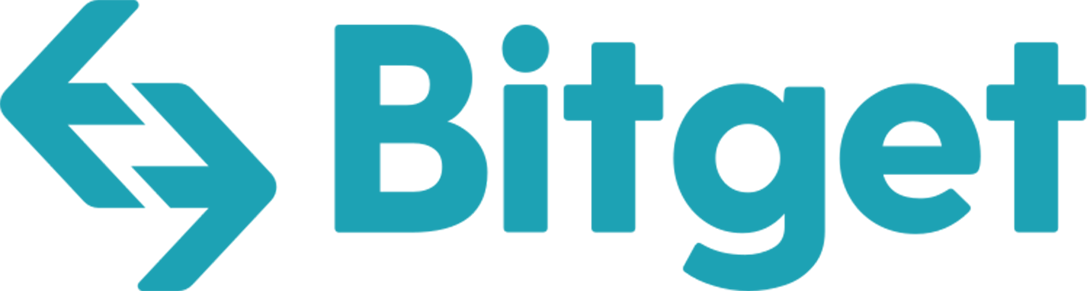













Komentar
Tuliskan Komentar Anda!