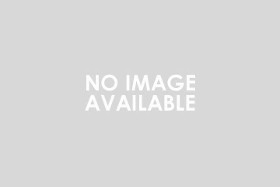
Tantangan dan Harapan dalam Reformasi Kepolisian
Prof Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa “60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek, jauh lebih baik daripada satu malam saja tidak ada polisi.” Kalimat ini menggambarkan realitas bahwa meskipun Polri memiliki kelemahan, masyarakat tetap membutuhkannya. Namun, satu tindakan negatif dari oknum tertentu bisa merusak reputasi institusi yang telah berjasa selama bertahun-tahun.
Dalam konteks ini, masyarakat cenderung menilai institusi Polri dengan standar yang tinggi. Setiap kali terjadi kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang, kritik publik sering kali menghujani lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Polri sangat besar.
Tuntutan reformasi Polri semakin menguat, terutama setelah beberapa insiden demonstrasi yang menimbulkan ketegangan antara aparat dan masyarakat. Berbagai media secara aktif melaporkan dan memberikan analisis mendalam tentang isu ini. Dalam hal ini, tokoh-tokoh seperti Komjen Pol (Purn) Arief Sulistyanto dan Benny K Harman memberikan kontribusi penting dengan usulan tiga dimensi utama reformasi serta sembilan poin reformasi jilid II.
Presiden Prabowo juga merespons dengan memberikan kepercayaan kepada Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan yang lebih radikal.
Setiap gelombang demonstrasi selalu menjadi sorotan publik. Meski Polri menjalankan tugasnya dengan pedoman menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa Polri terlalu represif. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia, etika demokratis, dan profesionalitas dalam setiap tindakan.
Max Weber dalam teorinya tentang legitimasi otoritas menekankan bahwa kekuasaan hanya bertahan jika didukung oleh rasio hukum dan pengakuan masyarakat. Dengan kata lain, Polri tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan koersif; mereka harus membangun legitimasi melalui keadilan dan penghormatan terhadap warga negara.
Profesionalitas aparat kepolisian sering didefinisikan sebagai kemampuan menjalankan tugas secara efektif dan sesuai standar hukum. Namun, dalam praktiknya, definisi ini menghadapi tantangan. Saat menjaga demonstrasi, Polri dihadapkan pada pilihan: apakah membiarkan kebebasan berekspresi sepenuhnya atau bertindak tegas dengan risiko melanggar hak asasi.
David Bayley dalam bukunya Police for the Future (1994) menyatakan bahwa legitimasi kepolisian bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan antara kontrol sosial dan perlindungan hak-hak individu. Pernyataan ini relevan dengan konteks Indonesia saat ini: profesionalitas Polri hanya bisa diakui jika mampu melindungi warga tanpa kehilangan kewibawaan dalam menjaga ketertiban.
Michel Foucault, filsuf Prancis, menekankan bahwa kekuasaan modern bekerja bukan hanya melalui dominasi fisik, tetapi juga melalui kontrol yang subtil dan pengawasan sosial. Dalam konteks Polri, profesionalitas seharusnya tidak direduksi pada kemampuan mengendalikan massa dengan kekuatan fisik, tetapi juga mencakup kapasitas membangun kepercayaan, transparansi, dan dialog dengan masyarakat.
Reformasi Kepolisian Sejak 1998
Reformasi Polri terjadi sejak 1998, ketika gelombang reformasi nasional menuntut perubahan mendasar dalam tata kelola kekuasaan. Pada tahap awal, desakan utama adalah pemisahan Polri dari ABRI/TNI, agar fungsi keamanan dalam negeri dijalankan oleh institusi sipil, bukan militer. Tonggak penting dicapai melalui Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 dan TAP MPR No.VII/MPR/2000, yang menegaskan pemisahan peran TNI dan Polri. Momentum ini kemudian diperkuat oleh lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi landasan hukum Polri modern.
Secara struktural, perubahan besar sudah dilakukan. Namun, secara kultural, perubahan itu berjalan lebih lambat. Polri masih menghadapi hambatan, seperti budaya kekuasaan yang hierarkis, sistem pengawasan yang lemah, dan kecenderungan aparat untuk menempatkan stabilitas sebagai prioritas tunggal dibanding hak-hak sipil.
Pasca-reformasi, Polri telah berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan dan modernisasi peralatan. Di sisi sumber daya manusia, berbagai program pendidikan dan peningkatan kapasitas juga dilakukan. Kelemahan pengawasan internal juga menjadi bukti bahwa reformasi belum sepenuhnya tuntas. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) maupun Divisi Propam sering kali dianggap tidak cukup kuat dalam menindak penyalahgunaan wewenang. Padahal, sejak awal reformasi, penguatan akuntabilitas merupakan tuntutan utama masyarakat.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Memasuki dekade 2000-an pertengahan, reformasi Polri diuji oleh berbagai kasus besar, seperti tragedi kekerasan dalam demonstrasi, penanganan terorisme, serta maraknya praktik korupsi di tubuh kepolisian. Publik mulai mempertanyakan sejauh mana Polri sungguh-sungguh berubah. Kasus rekening gendut, isu mafia hukum, hingga perlakuan represif terhadap demonstran memperlihatkan bahwa reformasi baru berjalan di tataran struktural, tetapi belum menyentuh ranah kultural dan etis.
Pada tahun 2010-an, muncul agenda modernisasi teknologi dan transparansi prosedur, seperti e-Tilang, SIM online, dan digitalisasi pelayanan publik. Secara administratif, langkah ini patut diapresiasi karena meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Namun, kritik masyarakat tetap mengemuka. Modernisasi prosedural tidak serta-merta mengubah cara pandang aparat dalam menghadapi warga. Demonstrasi besar, seperti aksi mahasiswa 2019 atau protes terkait Undang-Undang Cipta Kerja, kembali menunjukkan pola penanganan aparat yang dianggap terlalu represif.
Memasuki era 2020, tuntutan reformasi Polri semakin tajam. Kasus-kasus yang mencoreng institusi, seperti tragedi Kanjuruhan 2022, kasus Sambo 2022, serta berbagai laporan kekerasan aparat terhadap jurnalis dan mahasiswa, memperkuat persepsi publik bahwa Polri masih belum menuntaskan agenda reformasi. Kritik tajam dari akademisi, masyarakat sipil, hingga media massa menggema: Polri harus berani melakukan transformasi mendasar pada kultur organisasi, bukan hanya sekadar kosmetik kebijakan.
Peran Polri dalam Sistem Demokrasi
Dalam perspektif sejarah, reformasi Polri belum mencapai fase konsolidasi. Transformasi struktural memang penting, tetapi tanpa perubahan kultur dan penguatan pengawasan, maka legitimasi Polri akan terus dipertanyakan. Publik kini menuntut Polri tidak sekadar menjadi aparat penegak hukum, melainkan juga penjaga demokrasi dan keadilan sosial.
Filsuf politik John Rawls menekankan pentingnya keadilan sebagai fairness. Dalam kerangka Rawls, negara hanya dapat diterima oleh warganya apabila institusi-institusi yang ada memberikan jaminan perlakuan yang adil bagi semua. Jürgen Habermas menekankan konsep ruang publik sebagai arena di mana warga negara dapat mengartikulasikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Demonstrasi merupakan wujud ruang publik yang sah. Tugas Polri bukan membatasi, tapi menjaga agar tetap berlangsung aman dan tertib. Jika ruang publik ditutup dengan alasan keamanan, maka demokrasi kehilangan substansinya.
Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata yang menyentuh dua aspek utama: akuntabilitas internal dan partisipasi eksternal. Pertama, akuntabilitas internal. Hal ini dapat diperkuat melalui sistem pengawasan etik dan disiplin yang lebih tegas. Unit pengawasan internal tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus benar-benar berfungsi mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kedua, partisipasi eksternal. Pada konteks ini, penting diwujudkan dengan membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media. Polri tidak boleh bekerja dalam ruang tertutup. Transparansi dalam prosedur, kebijakan, dan evaluasi kinerja harus diperluas agar publik merasa memiliki akses dan kontrol.
Herman Goldstein, pencetus konsep problem-oriented policing, menegaskan bahwa kepolisian yang profesional adalah yang mampu menyelesaikan akar masalah sosial, bukan sekadar menanggapi gejala permukaan. Dalam konteks demonstrasi, ini berarti Polri perlu memahami substansi aspirasi masyarakat dan mendorong dialog, bukan hanya fokus pada pencegahan kericuhan.
Kehadiran Polri dalam sistem demokrasi modern tidak sekadar dipahami sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai salah satu pilar penting yang menjamin berlangsungnya kehidupan politik yang sehat. Demokrasi pada hakikatnya memberi ruang kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, serta hak warga negara untuk menyampaikan kritik kepada penguasa. Dalam konteks inilah, peran Polri menjadi krusial: bukan untuk membatasi kebebasan itu, melainkan menjaganya agar tetap berada dalam koridor hukum dan ketertiban.
Sejarah demokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa relasi antara kepolisian dan rakyat sering kali penuh ketegangan. Pada masa Orde Baru, polisi lebih dilihat sebagai perpanjangan tangan penguasa yang menjaga kepentingan politik rezim. Pasca-reformasi, publik berharap terjadi perubahan besar, yakni lahirnya kepolisian yang netral, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Namun, berbagai kasus kekerasan dalam demonstrasi maupun dugaan keberpihakan dalam kasus politik menimbulkan kesan bahwa reformasi Polri belum sepenuhnya menjawab tuntutan demokrasi.
Demokrasi membutuhkan kepolisian yang hadir sebagai mitra, bukan lawan; sebagai fasilitator ruang publik, bukan penutupnya. Kepolisian yang ideal dalam demokrasi adalah yang berlandaskan hukum, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana diingatkan oleh David Bayley, “Polri bukan entitas di luar masyarakat, tetapi bagian darinya. Jika hubungan itu rusak, maka kepercayaan publik runtuh, dan tanpa kepercayaan, demokrasi pun kehilangan fondasi.”
Mencari Keberanian Baru
Reformasi Polri yang telah berlangsung lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa perubahan struktural semata tidak cukup untuk menjawab ekspektasi masyarakat. Tantangan terbesar justru terletak pada keberanian moral dan politik institusi ini untuk keluar dari pola lama yang koersif menuju paradigma baru yang demokratis, transparan, dan humanis. Dalam titik inilah, Polri dituntut untuk menemukan kembali “keberanian baru” yang akan menentukan arah masa depannya.
Keberanian baru itu pertama-tama adalah keberanian untuk berbenah dari dalam. Reformasi internal yang menyentuh aspek kultur organisasi harus menjadi prioritas utama. Selama masih berpegang pada warisan budaya komando yang hierarkis dan menempatkan stabilitas di atas hak-hak warga, maka jurang ketidakpercayaan publik akan terus melebar. Dibutuhkan langkah nyata untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, menegakkan disiplin, serta memastikan bahwa setiap anggota Polri memahami dirinya bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai pelayan masyarakat.
Kedua, keberanian baru berarti kesediaan untuk terbuka pada kritik dan partisipasi eksternal. Demokrasi sehat hanya mungkin jika ruang publik diberi tempat, dan di dalam ruang itulah Polri harus hadir bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai penjaga. Menghadapi kritik publik bukanlah kelemahan, melainkan tanda kedewasaan institusional. Polri perlu berani membangun dialog terbuka dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media sebagai mitra dalam mengawal reformasi.
Lebih jauh lagi, keberanian baru adalah keberanian untuk mendefinisikan ulang relasi dengan masyarakat: mengubah paradigma dari “mengendalikan masyarakat” menjadi “bekerja bersama masyarakat.” Dalam kerangka lebih luas, keberanian baru Polri adalah keberanian untuk meneguhkan dirinya sebagai institusi yang berdiri di atas hukum dan demokrasi. Keberanian baru yang dituntut dari Polri adalah keberanian untuk melangkah melampaui kepentingan jangka pendek, menuju cita-cita besar: kepolisian yang profesional, humanis, dan demokratis.



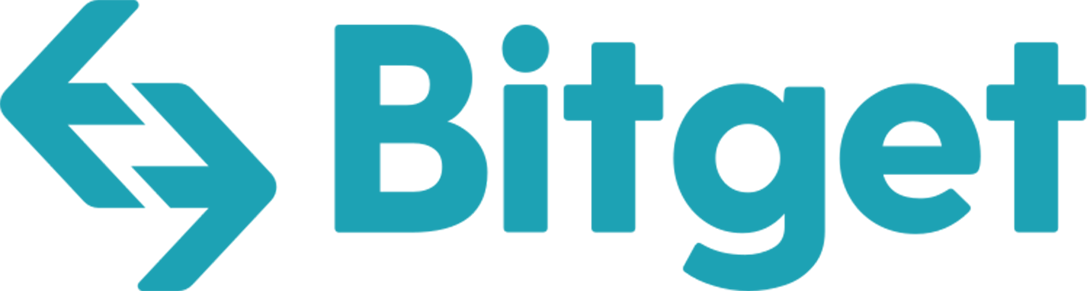













Komentar
Tuliskan Komentar Anda!